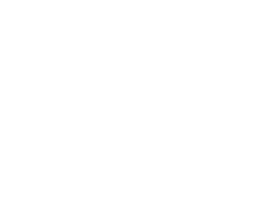Dilema Profesional Muda di BUMN: Epilog Kasus ASDP

Kenny Wiston
Kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP menjadi preseden yang mengusik nalar hukum korporasi di Indonesia. Di tengah kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan—laba melonjak dari Rp326 miliar (2021) ke Rp637 miliar (2023), pendapatan naik menjadi Rp5 triliun, dan peringkat 7 BUMN terbaik—mantan direksi justru dituntut 8,5 tahun penjara karena dugaan merugikan negara Rp1,25 triliun.
Masalahnya bukan pada audit, melainkan pada siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Undang-undang mengatur bahwa kerugian negara hanya sah jika dihitung oleh BPK atau BPKP. Namun dalam kasus ini, angka fantastis Rp1,25 triliun dihitung auditor internal KPK bersama seorang akademisi tanpa sertifikasi penilai publik. BPK menyatakan tidak pernah diminta melakukan audit, dan ketika hadir sebagai saksi ahli, lembaga ini justru menegaskan tidak ditemukan kerugian negara signifikan—hanya opportunity loss atas dua kapal senilai Rp4,8–10 miliar.
Lebih jauh, penilai publik bersertifikat menyatakan akuisisi dilakukan di bawah nilai pasar: valuasi independen Rp2,09 triliun, sementara ASDP membayar Rp1,27 triliun. Artinya negara untung, bukan rugi. Namun kesaksian ini tidak menjadi dasar tuntutan. Di sisi lain, elemen pokok korupsi tidak pernah muncul di persidangan: Tidak ada aliran dana ilegal (versi PPATK dan KPK), Tidak ada penerima suap, Proses akuisisi disetujui organ perseroan, dan Aset yang dibeli menghasilkan lonjakan laba dan pendapatan.
Secara teori, business judgment rule melindungi keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, transparan, memiliki dasar hukum, dan bertujuan meningkatkan nilai perusahaan. Fakta kinerja ASDP pasca-akuisisi justru menunjukkan keberhasilan strategi korporasi, bukan manipulasi. Namun persidangan memperlihatkan masalah mendasar sistem hukum: fakta persidangan dianggap tidak relevan dengan dakwaan. Kuasa hukum mengungkapkan tuntutan jaksa identik dengan BAP awal, seolah proses persidangan hanya formalitas. Ini menciptakan citra “putusan dulu, fakta belakangan”.
Fenomena ini menimbulkan chilling effect yang berbahaya bagi profesional muda di BUMN. Pesannya jelas: keberanian mengambil keputusan bisnis dapat dipidana, meskipun tanpa kerugian negara dan tanpa korupsi. Akibatnya, muncul dua ekstrem berbahaya:
- manajemen konservatif yang anti-risiko, membuat BUMN stagnan, atau
- manajemen oportunis yang berani tetapi pandai menyamarkan korupsi.
Keduanya merugikan negara. Lebih fatal lagi, kriminalisasi keputusan bisnis membuat talenta terbaik enggan bekerja di BUMN. Di sektor swasta, inovasi dihargai. Di BUMN, inovasi bisa berujung rompi oranye. Kasus ASDP menjadi ujian besar bagi peradilan: apakah hukum mampu membedakan risiko bisnis dari tindak pidana korupsi? Apakah perhitungan kerugian negara tunduk pada standar hukum, atau pada interpretasi lembaga penegak hukum?
Putusan hakim akan menjadi penentu arah kebijakan negara. Apabila berbasis pada hukum pembuktian, perkara ini seharusnya berakhir dengan putusan bebas. Namun, apabila semata-mata berbasis pada dakwaan, hal tersebut menjadi alarm keras bahwa upaya transformasi BUMN hanya sebatas slogan, karena setiap langkah strategis berpotensi ditafsirkan sebagai tindakan pidana.
Pada akhirnya, dilema profesional muda di BUMN adalah dilema keadilan itu sendiri: ketika hukum tidak lagi membedakan antara kesalahan dan keputusan bisnis, maka yang dihukum bukan hanya individu—tetapi masa depan keberanian berinovasi di perusahaan negara.