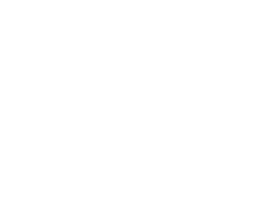Elegi Senja di Gerbang Ganesha: Mengenang Rene Conrad
 Kenny Wiston
Kenny Wiston
Senja turun perlahan di Gerbang Ganesha, seakan tahu bahwa di tempat ini ada kisah yang tidak pernah selesai. Bayang pepohonan memanjang di aspal, lampu-lampu kampus mulai menyala, namun justru keheningan terasa paling nyaring. Karena setiap sore seperti ini, ada satu nama yang kembali dipanggil oleh ingatan: Rene Louis Conrad.
Ia adalah mahasiswa Teknik Elektro ITB—berambut gondrong, cerdas, penuh tawa yang mudah pecah, dan pandangan hidup yang selalu lebih besar dari usianya. Pada masa ketika pemikiran kritis dicurigai, dan rambut gondrong dianggap simbol pembangkangan, ia tumbuh sebagai representasi kebebasan seorang anak muda.
Hari itu, di era 1970-an, kampus menggelar pertandingan sepak bola antara ITB dan Akpol. Mestinya sepak bola hanya soal riuh stadion kecil dan sorak-sorai biasa. Namun ketika gengsi bersanding dengan senjata, ejek-mengejek berubah menjadi bara. Arogansi aparat menjelma ancaman. Mereka datang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pihak yang merasa berhak menaklukkan.
Di tengah suasana tegang itu, Rene melintas di Gerbang Ganesha. Ia bukan peserta pertandingan. Ia tidak mengejek siapa pun. Ia hanya berjalan melewati sore yang seharusnya biasa. Tetapi peluru tidak pernah peduli siapa yang bersalah. Peluru tak punya logika—hanya arah.
“Dor.”
Dalam sekejap, tubuh Rene jatuh. Suara tembakan merobek udara, merobek kewarasan, merobek batas antara aparat dan kemanusiaan. Darahnya membasahi aspal tepat di depan gerbang yang selama ini menjadi lambang kebebasan berpikir.
Bandung pun membara. Ribuan mahasiswa turun ke jalan. Teriakan menggema: “Arogansi harus dihentikan!” Negara menjawab dengan gas air mata, rotan, dan peluru lagi. Dan di tengah asap yang naik ke langit, nama Rene berubah menjadi simbol—bahwa kesewenang-wenangan bisa menembak siapa saja, bahkan orang yang sekadar melintas.
Puluhan tahun telah berlalu. Generasi berganti. Rambut gondrong tak lagi menjadi ancaman negara. Tapi di Gerbang Ganesha, ketika senja menghitam dan angin berhembus pelan, ingatan itu tetap hidup. Setiap langkah mahasiswa yang melewati gerbang ini seharusnya tahu: kebebasan yang mereka nikmati pernah dibayar dengan darah seorang anak muda.
Malam akhirnya tiba. Tapi kisahnya tidak pernah padam.
Senja turun perlahan di Gerbang Ganesha, seakan tahu bahwa di tempat ini ada kisah yang tidak pernah selesai. Bayang pepohonan memanjang di aspal, lampu-lampu kampus mulai menyala, namun justru keheningan terasa paling nyaring. Karena setiap sore seperti ini, ada satu nama yang kembali dipanggil oleh ingatan: Rene Louis Conrad.
Ia adalah mahasiswa Teknik Elektro ITB—berambut gondrong, cerdas, penuh tawa yang mudah pecah, dan pandangan hidup yang selalu lebih besar dari usianya. Pada masa ketika pemikiran kritis dicurigai, dan rambut gondrong dianggap simbol pembangkangan, ia tumbuh sebagai representasi kebebasan seorang anak muda.
Hari itu, di era 1970-an, kampus menggelar pertandingan sepak bola antara ITB dan Akpol. Mestinya sepak bola hanya soal riuh stadion kecil dan sorak-sorai biasa. Namun ketika gengsi bersanding dengan senjata, ejek-mengejek berubah menjadi bara. Arogansi aparat menjelma ancaman. Mereka datang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pihak yang merasa berhak menaklukkan.
Di tengah suasana tegang itu, Rene melintas di Gerbang Ganesha. Ia bukan peserta pertandingan. Ia tidak mengejek siapa pun. Ia hanya berjalan melewati sore yang seharusnya biasa. Tetapi peluru tidak pernah peduli siapa yang bersalah. Peluru tak punya logika—hanya arah.
“Dor.”
Dalam sekejap, tubuh Rene jatuh. Suara tembakan merobek udara, merobek kewarasan, merobek batas antara aparat dan kemanusiaan. Darahnya membasahi aspal tepat di depan gerbang yang selama ini menjadi lambang kebebasan berpikir.
Bandung pun membara. Ribuan mahasiswa turun ke jalan. Teriakan menggema: “Arogansi harus dihentikan!” Negara menjawab dengan gas air mata, rotan, dan peluru lagi. Dan di tengah asap yang naik ke langit, nama Rene berubah menjadi simbol—bahwa kesewenang-wenangan bisa menembak siapa saja, bahkan orang yang sekadar melintas.
Puluhan tahun telah berlalu. Generasi berganti. Rambut gondrong tak lagi menjadi ancaman negara. Tapi di Gerbang Ganesha, ketika senja menghitam dan angin berhembus pelan, ingatan itu tetap hidup. Setiap langkah mahasiswa yang melewati gerbang ini seharusnya tahu: kebebasan yang mereka nikmati pernah dibayar dengan darah seorang anak muda.
Malam akhirnya tiba. Tapi kisahnya tidak pernah padam.